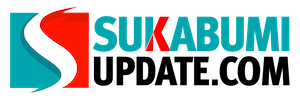SUKABUMIUPDATE.com - Sekretaris Jenderal Asosiasi Media Siber Indonesia atau AMSI Wahyu Dhyatmika mengatakan ekosistem media digital di tanah air dipandang belum ideal untuk membangun jurnalisme yang berkualitas.
Menurutnya, ekosistem digital saat ini masih menyamaratakan dengan publisher pembuat konten sehingga tidak melihat isi atau kualitas medianya.
Ia mencontohkan model bisnis programmatic ads atau iklan otomatis, yang diukur hanya berdasar pageview. Kondisi ini, katanya, mendorong media untuk melupakan isi berita dan hanya fokus pada apa yang diinginkan pembacanya untuk mencari klik sebanyak-banyaknya, tanpa mempertimbangkan kualitas berita.
“Jangan sampai perubahan ekosistem media, membuat publik kehilangan sumber informasi yang terpercaya” kata Wahyu Dhyatmika saat diskusi publik tentang Tantangan dan Peluang Media Digital, yang diselenggarakan Tempo Institute, dalam rangka mengawali kegiatan Pelatihan (bootcamp) Media Digital Program Independent Media Accelerator (IMA), Selasa, 19 Juli 2022.
Jika itu terjadi, lanjutnya, publik tidak bisa lagi membedakan mana fakta yang terverifikasi, opini, hoaks, atau kabar info berbayar. Alhasil, publik tidak bisa merumuskan sebuah pendapat yang berdasarkan informasi yang faktual.
Wahyu Dhyatmika juga memaparkan ekosistem aspek penting lainya antara lain adaptasi teknologi, adaptasi format, dan adaptasi mindset, supaya roh independen itu tidak sampai hilang. Dengan banyaknya kemunculan media digital, media cenderung lebih suka membuat berita yang hanya disukai khalayak tanpa ada unsur edukasi atau kritisnya.
Setali tiga uang, Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Sasmito Madrim juga melihat kualitas jurnalisme masih menjadi persoalan. Indikasinya dapat dilihat, dari banyaknya laporan yang masuk ke Dewan Pers. Dalam satu tahun terakhir setidaknya ada 600 laporan terkait ketidakprofesionalan atau soal kode etik jurnalistik.
Ia mengungkapkan kualitas media dan kualitas jurnalisme tidak bisa disama-ratakan. Sebab pola kaderisasi dan pembinaan jurnalis beragam. Ada media yang saat menerima wartawannya harus melalui proses pelatihan, tapi tak jarang media menerjunkan langsung wartawan mudanya ke lapangan tanpa pelatihan.
“Di satu sisi, banyak juga media yang tampil dengan keunikannya, seperti halnya Project Multatuli, Konde, Magdalene dan sebagainya,” papar Sasmito.
Menurut Wahyu di tengah persaingan yang ketat sebuah media memang harus memiliki diferensiasi yang kuat. Ia melihat tiga media itu memang memiliki visi yang jernih, apa yang akan mereka lakukan, jenis jurnalisme apa yang mereka ingin sajikan, dan segmen audiens seperti apa yang ingin mereka layani.
“Kita ingin melihat media tersebut dalam 3-5 tahun ke depan, apa inovasi tersebut memiliki napas panjang?” terangnya.
Ia berharap inovasi seperti ini tumbuh lebih banyak lagi, serta menyuburkan inovasi yang sudah ada. Itulah yang dimaksud ekosistem media digital.
Menurutnya, dari sana dapat dilihat apakah model bisnis yang ada, bisa tahan dalam waktu yang panjang. Apakah stakeholder pada ekosistem media kita sekarang menyadari pentingnya keberadaan mereka, dan bisa menjadi partner yang membantu keberlanjutan media baru.
Pada sisi internal, apakah media baru ini mempunyai kapasitas manajemen yang tepat, yang bisa membantu mereka melewati fase krusial pada tahun awal pendirian.
“Kita bersyukur ada inisiatif semacam Independent Media Accelerator yang memberi dukungan pada media-media baru. Namun itu belum cukup karena kita juga harus memastikan bibit yang unggul ini bisa tumbuh pada tanah yang juga subur,“ kata Wahyu.
Menurutnya, ekosistem media yang baik, esensinya harus kembali kepada roh jurnalisme itu sendiri. “Jangan sampai jurnalisme itu tergelincir, atau diturunkan statusnya hanya sebatas konten,” katanya.
Ini penting agar mereka tetap eksis dan harus tetap bisa hadir untuk publik. Sebab fungsi jurnalisme itu, melayani kepentingan publik serta menjadi mata dan telinga publik, untuk mengawasi kegiatan negara serta menjamin akuntabilitas pemerintah.
“Jika fungsi jurnalisme itu hilang atau tergerus, maka tidak ada model bisnis yang bisa memastikan keberlangsungannya, dan yang rugi kita semua,” kata dia.
Ia pun memaparkan variabel sebuah ekosistem digital yang ideal berangkat dari fungsi dan tujuan akhir yang ingin dicapai. Salah satunya, ada kesamaan persepsi pemangku kepentingan atau stakeholder tentang signifikansi jurnalisme.
“Jadi semua stakeholder, seperti publisher, penerbit media, asosiasi jurnalis wartawannya dan publik harus memiliki persepsi yang sama, bahwa yang harus diselamatkan adalah jurnalisme yang berkualitas,” tuturnya.
Ia memberi contoh sederhana bagaimana ekosistem yang ideal itu berangkat dari persamaan persepsi. Misalnya dengan kesadaran, bahwa jurnalisme itu tidak bisa gratis. Sehingga aktivitas mencari, mengolah informasi, dan menyajikannya menjadi sebuah berita terverifikasi, terkonfirmasi dan independen, semua kegiatan itu membutuhkan biaya.
“Jika kita semua percaya itu penting, maka kita tidak boleh segan mengeluarkan uang. Maka hal itu memungkinkan model bisnis itu menjadi subur,” kata Wahyu.
Saat ini model bisnis yang paling mengemungkinkan di media adalah iklan. Jika publik dan stakeholder memiliki kesadaran, bahwa jurnalisme itu penting. Maka sumber pendapatan untuk menopang jurnalisme, tidak hanya iklan, tetapi bisa melalui langganan, membership, hibah, atau bisa juga dengan model pembelian konten oleh perusahaan teknologi digital.
“Jika kita berangkat dari sana, maka separuh dari ekosistem yang ideal itu sudah terbentuk,” kata pria yang disapa Komang ini.
Sebagai Sekjen AMSI, Wahyu mengaku sering bertemu dengan penerbit media lokal di daerah dan mendengar keluhan mereka. Mereka mengeluh ekosistem sekarang dinilai tidak memberikan ruang atau insentif bagi mereka, bagi media yang benar. Para pemberi iklan sering kali tutup mata tentang garis api. Mereka tidak mau memberikan insentif untuk media yang berusaha kritis. Media yang menjadi watchdog, dan mengkritik pejabat daerah justru tidak mendapat kue iklan.
Sementara Sasmito melihat hal itu akibat ketidaktransparanan pihak pemberi iklan. Pemerintah daerah hanya mau beriklan pada kelompok media tertentu, atau kelompok yang hanya menjadi bagian lingkaran politik mereka.
“Jangan sampai ini menjadi kesepakatan sebagian pihak, apalagi menjelang Pemilu 2024,” katanya.
Diskusi ini juga menyoroti gejala banyaknya media lokal yang bergantung dari pemerintah daerah. Menurut keduanya hal itu sebenarnya tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah jika iklan tersebut mempengaruhi independensi dan mutu media dan jurnalisnya.
Sasmito berharap semua pihak hendaknya mendorong agar iklan tidak dikaitkan dengan pemberitaan. Ia mengatakan perlu ada political will, misalnya, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan edaran agar pemerintah daerah tidak mengaitkan iklan dengan pemberitaan.
Mengatasi ketidakidealan ekosistem media, Dewan Pers bersama sejumlah mitra sedang mengupayakan adanya pemeringkatan media. Baik terhadap media mainstream atau media alternatif. Selama ini pemeringkatan media, hanya dilihat dari berapa banyak orang melihat dan membaca, seperti dilakukan Alexa.
Kali ini pemeringkatan akan dilakukan dengan menambah banyak indikator seperti memasukan, bagaimana media memenuhi kode etik Jurnalisme. Termasuk bagaimana media itu memenuhi standar sebagai perusahaan pers, seperti memberikan gaji yang layak dan asuransi.
Selain itu, pemeringkatan ini diharapkan bisa membantu masyarakat untuk memilih media yang berkualitas. Juga dari sisi pengusaha dan pemerintah, jika ingin beriklan bisa melihat apa saja media yang berkualitas sehingga transparansinya harus dibangun.
Pada kesempatan itu Qaris Tajudin selaku moderator diskusi menyampaikan bahwa saat ini Tempo Institute tengah membuka peluang bagi 20 media daerah untuk mengikuti fellowship dan pelatihan bagi media kecil di daerah. Selain pelatihan, juga ada pendanaan untuk usulan proyek perbaikan media sebesar Rp 100 juta. Kegiatan itu di bawah program bernama Independent Media Accelerator, di mana pendaftaran dapat dilihat di media sosial dan website Tempo Institute.
SUMBER: TEMPO.CO
Editor : Oksa Bachtiar Camsyah