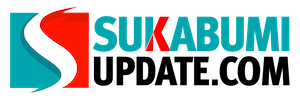SUKABUMIUPDATE.com - Mengapa Jepang tidak menerapkan karantina wilayah? Sejumlah teman saya dari seluruh dunia menanyakan hal itu kepada saya berulang kali.
Dilansir dari suara.com, tak mengherankan pertanyaan itu muncul, terutama jika melihat pandemi yang terjadi di Eropa.
Namun kemungkinan besar itu adalah pertanyaan yang keliru karena Taiwan, Hong Kong. Korea Selatan, dan mayoritas wilayah China tidak pernah benar-benar ditutup.
Bagi orang-orang yang ingin memahami apa yang terjadi di Jepang, pertanyaan yang sebenarnya penuh teka-teki adalah tentang jumlah tes Covid-19 yang sangat sedikit.
Selisih jumlah tes yang digelar Jepang bisa berbeda satu digit dibandingkan Jerman atau Korea Selatan. Ambil contoh Tokyo, kota dengan populasi 9,3 juta orang dan merupakan pusat epidemi Covid-19 di Jepang.
Sejak Februari lalu, hanya 10.981 orang di kota itu yang sudah menjalani tes Covid-19. Dari jumlah itu, sekitar 4.000 orang di antaranya positif mengidap penyakit tersebut.
Namun angka itu mengejutkan, karena jumlah tes yang dilakukan sangat kecil, sedangkan persentase orang yang dinyatakan positif Covid-19 begitu tinggi.
Angka itu memberi gambaran bahwa orang-orang di Jepang yang menjalani tes adalah mereka yang sudah jatuh sakit.
Faktanya, pedoman resmi untuk dokter di negara itu menyebut bahwa mereka hanya boleh merekomendasikan seseorang menjalani tes jika orang tersebut mengalami pneumonia atau infeksi paru-paru.
Menurut Kementerian Kesehatan Jepang, itulah alasan mengapa jumlah tes yang mereka lakukan hanya setengah dari kapasitas, bahkan setelah ada kebijakan resmi agar tes digelar lebih masif.
Fakta ini kemudian memunculkan sejumlah cerita menarik tentang mereka yang berusaha menjalani tes Covid-19.
Jordain Haley adalah warga Amerika Serikat yang bekerja di Jepang sebagai analis bisnis dan penerjemah sukarela. Melalui Skype, dia berkisah tentang kawannya, yang tak fasih berbahasa Jepang, yang berusaha menjalani tes.
Pada 10 April lalu, kawannya demam dan batuk. Dia menunggu empat hari seperti yang diatur dalam pedoman tes Covid-19.
"Ketika itu dia sulit bernapas dan pening karena kekurangan oksigen," kata Jordain
"Saya menghubungi pusat kontak Covid. Mereka menolak membantu. Mereka berkata, jika kawan saya sakit, maka saya seharusnya menghubungi ambulans," tuturnya.
Pada 15 April, kawannya datang ke klinik yang bisa melakukan pemeriksaan X-ray dada. Dokter di klinik itu menyebut kemungkinan teman Jordain mengidap Covid-19.
Akan tetapi, gejala medis yang dialaminya tidak sedemikian buruk sehingga perlu dilarikan ke rumah sakit. Dokter itu memulangkan dan meminta kawan Jordain untuk isolasi mandiri.
Pada malam keesokan harinya, Jordain mendapat telepon dari kawannya itu. Dia mengaku stres.
"Saya mendengar suara sirine ambulans saat telepon itu. Dia batuk dan suara napasnya nyaring sehingga saya tak mendengar jelas apa yang dia katakan," kata Jordain.
"Setelah dua jam, barulah rumah sakit menerimanya. Sepanjang waktu itu, pernapasannya semakin buruk," tuturnya.
Pihak rumah sakit melakukan X-ray dada ulang dan meminta temannya menjalani tes Covid-19 di pusat kesehatan setempat. Namun, sang dokter tidak bersedia memberi surat rekomendasi. Sebaliknya, dia dipulangkan menggunakan taksi.
"Mereka bilang kawan saya mesti membuka jendela taksi dan semuanya akan baik-baik saja," kata Jordain.
Pada 17 April, Jordain mengontak pusat kesehatan setempat. Selama dua jam dia dirujuk ke sejumlah bagian.
Jordain menjawab beberapa pertanyaan sebelum akhirnya dia berhasil membuatkan janji tes untuk kawannya. Tapi dia mendapat peringatan.
"Dia harus masuk dari pintu samping. Dia tidak boleh berkata kepada siapapun di mana lokasi tes. Itu bisa memicu kekacauan," ujar Jordain mengulang peringatan yang diterimanya.
Di luar konteks tekanan yang membuat seseorang menanggap kesehatannya dalam ancaman, mengapa semua kisah ini penting? Lagi pula angka kematian akibat Covid-19 di Jepang sangat rendah, di bawah 400 orang.
Di media sosial saya kerap diberitahu bahwa Jepang mengidentifikasi siapa yang benar-benar membutuhkan bantuan dan layanan kesehatan di negara itu mumpuni.
Dan itulah yang disebut mengapa sangat sedikit orang meninggal akibat penyakit ini.
Semua pemaparan tadi tidak keliru, menurut Kenji Shibuya, seorang profesor di Kings College London.
"Dari sudut pandang dokter, itu masuk akal," ujarnya.
"Lupakan kasus dengan gejala ringan dan fokuslah pada kasus dengan gejala akut. Selamatkan banyak nyawa. Pusatkan tes untuk orang-orang yang bergejala," kata dia.
Namun dari sudut pandang ilmu kesehatan masyarakat, menurut Shibuya, penolakan Pemerintah Jepang untuk menggelar lebih banyak tes sangat berisiko. Shibuya merujuk sebuah kajian yang dikerjakan Universitas Keio, Tokyo.
Pekan lalu, rumah sakit di kampus itu menerbitkan hasil penelitian mengenai tes Covid-19 yang dilakukan terhadap pasien tanpa gejala dan yang dirawat bukan dengan prosedur Covid.
Hasilnya, menurut penelitian itu, sekitar 6 persen pasien dinyatakan positif mengidap Covid-19.
Itu adalah contoh kecil dan tidak bisa digeneralisasi. Tapi Shibuya tetap menganggap hasil kajian itu 'sangat mengejutkan'.
"Kita benar-benar melewatkan banyak kasus tanpa gejala dan kasus dengan pasien yang mengalami gejala ringan," ujarnya.
"Jelas bahwa ada penyebaran virus di masyarakat. Saya sangat mencemaskan situasi ini."
Berapa banyak kasus yang dilewatkan? Dia tidak yakin. Namun merujuk penelitian Keio, Shibuya memperkirakan angkanya bisa 20 hingga 50 kali lebih besar dari data resmi. Artinya, antara 280 hingga 700 ribu orang di Jepang berpotensi terinfeksi Covid-19.
Tanpa tes yang lebih banyak, sulit untuk mengetahui angka persisnya. Namun bukti-bukti yang dikumpulkan dari beragam testimoni presonal mendukung gagasan bahwa jumlah kasus Covid-19 di negara itu lebih besar.
Di antara kasus kematian yang rendah di Jepang, dua di antaranya menimpa pelawak terkenal, Ken Shimura, dan aktris Kumiko Okae.
Kasus kematian lainnya juga menimpa orang-orang ternama seperti tujuh pesumo, pemandu acara televisi, dua mantan atlet bisbol, dan penulis film.
"Saat ini 70 hingga 80 persen kasus infeksi baru yang tercatat di Tokyo tidak muncul dalam klaster baru," kata Yoshitake Yokokura, pimpinan Asosiasi Kesehatan Jepang.
"Kita perlu melakukan lebih banyak tes dan mendapatkan hasilnya secepat mungkin," tuturnya.
Merujuk data resmi, jumlah kasus baru di Tokyo menurun selama sepekan terahir. Apa ini berita menggembirakan? Belum tentu.
"Saya ingin percaya bahwa jumlah benar-benar menurun, tapi jumlah tes yang dilakukan tidak cukup untuk mendukung data tersebut," kata Yokokura.
Situasi ini berdampak langsung pada kemampuan Jepang mencabut status darurat kesehatan yang akan berakhir 6 Mei mendatang.
"Tidak mungkin mencabut status itu dalam situasi seperti ini," kata Yokokura.
"Untuk mencabutnya, harus ada tren penurunan kasus yang berkelanjutan dan angka penularan yang juga harus di bawah itu," tuturnya.
Pekan ini Jepang masuki periode Golden Week atau periode libur tahunan terpanjang. Menurut keterangan Gubernur Okinawa Denny Tamaki, sekitar 60.000 orang sudah memesan penerbangan untuk berlibur ke wilayahnya.
Tamaki memohon mereka untuk membatalkan rencana itu.
"Saya minta maaf harus mengatakan ini tapi Okinawa sedang di bawah status darurat. Tolong batalkan perjalanan Anda ke Okinawa sekarang," ujarnya di media sosial.
Pekan depan cuaca di Jepang diperkirakan cerah dan panas. Banyak orang bakal terdorong untuk menuju ke pantai atau gunung, tanpa mengetahui beberapa di antara mereka bakal tertular virus corona.
Profesor Shibuya berkata Jepang perlu meninggalkan strategi penanganan Covid-19 yang saat ini dan meningkatkan jumlah tes.
"Tanpa tes yang luas, sangat sulit mengakhiri pandemi ini," tuturnya.
Sumber: Suara.com
Editor : Budiono