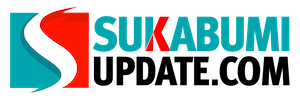SUKABUMIUPDATE.com - Hari ini, Sabtu (14/4), di di Omah Btari Sri, Ragunan Jakarta, sekelompok aktivis muda Islam, mengadakan tahlilan untuk mendoakan Djohan Effendi, Mensesneg Era Presiden Abdurrahman Wahid, yang meninggal di Geelong, Australia, 17 November 2017. Acara tahlilan ini, sekaligus untuk menghidupkan kenangan terhadap para pembaharu Islam sezaman Djohan (yang juga koleganya) seperti Abdurrahman Wahid, Nurcholish Madjid, Moeslim Abdurrahman, Utomo Dananjaya, Ekky Syachruddin, Ismed Nasir, Imaduddin Abdulrahim, Ahmad Wahib, Syu’bah Asa, Munawir Sjadzali, Mukti Ali, dan Harun Nasution.
Mereka, para tokoh pemikir tersebut, telah membuka wawasan kita bangsa Indonesia akan pentingnya menempatklan Islam dalam bingkai kemodernan, pluralisme, kebhinekaan, kerukunan, dan toleransi kehidupan beragama. Masing-masing dari mereka punya peran yang unik.
Djohan, misalnya, berperan mengembangkan dialog antariman. Djohan dikenal sebagai “pelintas batas†karena ia merintis dialog antariman untuk menemukan kesamaan pandangan terhadap kemanusiaan dan keindonesiaan. Bagi Djohan kemanusiaan adalah inti dari tujuan semua agama. Bersama Ismed Nasir, Djohan menerbitkan buku catatan harian Ahmad Wahib “Pergolakan Pemikiran Islam†yang sangat menghebohkan di tahun 1981.
Penerbikan buku tersebut butuh keberanian sendiri karena niscaya akan menghadapi resiko reaksi negatif dari kalangan Islamis. Djohan dan Ismed mampu bertahan menghadapi segala macam reaksi negatif tersebut. Dukungan majalah Tempo yang saat itu “digawangi†Syu’bah Asa – menjadi laporan utama dua kali penerbitan Tempo -- menyebabkan buku “Pergolakan Pemikiran Islam†makin populer. Renungan-renungan Wahib yang mendobrak kebekuan pemikiran Islam pun menjadi wacana publik. Dampaknya luar biasa. Kelompok kelompok diskusi yang mengusung liberalisme Islam tumbuh setelah penerbitan buku itu. Salah seorang yang giat menumbuhkan diskusi bertema Modernitas dan Moderasi Islam itu adalah Ekky Sachrudin, Dubes Indonesia untuk Kanada (2001-2004).
Sementara Abdurrahman Wahid berupaya mempribumikan Islam, yang kini dikenal dengan Islam Nusantara. Gagasan Gus Dur untuk mengganti Assalamualaikum dengan Selamat Pagi, sebetulnya dalam rangka pribumisasi Islam. Kini kita melihat fakta, kata “Assalamualaikum†– alih-alih sebagai doa seperti sabda Rasul – malahan berubah menjadi identitas politik kelompok tertentu yang potensial menyebabkan disentegrasi nasional. Kata Salam tidak lagi bernuansa damai seperti harapan Rasul, tapi telah menjadi pemicu radikalisme.
Kata Salam, kata kelompok radikal, hanya untuk orang yang Islamnya jelas dan tak diragukan (sesuai pandangannya). Kata salam haram tertuju pada orang kafir. Catat, yang dimaksud kafir adalah orang nonislam dan orang Islam yang tidak seideologi dengannya.
Nurcholish telah menyodorkan modernisasi pemikiran Islam. Bagi Cak Nur Islam adalah moderasi, kedamaian, dan pengetahuan universal. Jargon “Islam Yes and Politik No†dari Cak Nur, kini terbukti kebenarannya. Ketika Islam berpelukan dengan Politik yang terjadi adalah Islam sebagai instrumen kekuasaan. Dan, kekuasaan sangat rentan dengan corruption. Corruption bukan sekedar bribery/finansial , tapi juga ideologi dan isme. Islamisme inilah yang kini tengah menghantui bangsa kita.
Bersama Harun Nasution, rektor IAIN Jakarta, yang berupaya membangkitkan “Islam Rasional†-- Cak Nur mengajak kita untuk melihat Islam dari semangat menggali ilmu pengetahuan. Seperti Islam di era penemu sainstek (Ibnu Sina, Al-Kwarizmi, Al-Jabar, Al-Battani, dll).
Dalam kondisi seperti itulah, Munawir Sjadzali sebagai menteri agama menawarkan fikih kontekstual. Munawir, misalnya, menyampaikan gagasan warisan dalam hukum fikih berbasis keseteraan gender. Fifty-fifty antara pria dan wanita. Bukan 70-30 persen seperti hukum waris fikih konvensional.
Semua gagasan di atas, tentu saja harus dibingkai dengan tauhid yang membumi (Imaduddin Abdulrahim). Tauhid yang berbasis kemanusiaan. Karena manusia adalah khalifah Allah di muka bumi. Karena itu, tulis Bang Imad, taukhid harus berimplikasi kepada kesamaan derajat kemanusiaan dengan menghilangkan perbedaan suku dan etnis. Hanya Allah yang tertinggi derajatnya. Manusia semua sama.
Akhirnya, para pembaharu itu tak akan tumbuh jika tanpa penyemai bibit yang baik seperti Mukti Ali dan manajer brilian seperti Utomo Danajaya. Mereka semua mempunyai peran strategis dalam mengusung Pembaharuan Pemikiran Islam.
Dalam kerangka itulah, kita perlu mengapresiasi para pembaharu tersebut. Kenapa? Karena zaman telah berubah. Terutama sejak era reformasi, di mana “kelompok Islam konservatif dan radikal†melalui berbagai upaya mengusung ideologi islamisme. Islamisme itu kini, tragisnya, telah diadopsi partai politik tertentu dan berpelukan dengan tokoh-tokoh yang syahwat politik dan kekuasaannya menggelegak.
Hasilnya, simbiose islamisme dan politik itu sebagai berikut:Â Radikalisme Islam menguat. Sendi-sendi kebhinekaan runtuh. Kerukunan beragama terancam. Toleransi kehidupan pudar.
LIPI (Anas Saidi, 2016) dalam penelitiannya, menemukan kalangan anak muda Indonesia makin mengalami radikalisasi secara ideologis dan makin tidak toleran; sementara perguruan tinggi banyak dikuasai oleh kelompok garis keras. Ada perguruan tinggi negeri umum, misalnya, yang memberikan beasiswa khusus tanpa tes untuk lulusan SMA/Aliyah yang hafal Qur’an. Di samping itu, kini muncul ide pemisahan kelas perempuan dan laki-laki di perguruan tinggi umum. Bahkan, konon, sudah ada PTN yang melakukan pemisahan ruang kuliah mahasiswa berbasis gender tersebut.
Di pihak lain, survei Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) Jakarta, 2010-2011, menemukan fenomena mengejutkan: 50% pelajar di DKI Jakarta setuju radikalism; 25% siswa dan 21% guru menyatakan Pancasila tidak relevan lagi diajarkan di sekolah . Sementara 84,8% siswa dan 76,2% guru setuju dengan penerapan syariat Islam di Indonesia. Yang setuju dengan kekerasan untuk solidaritas Islam 52,3% dan penggunaan bom 14,2%. Adapun survei The Pew Research Center pada 2015 lalu, menemukan bahwa sekitar 4 % atau sekitar 10 juta orang Indonesia mendukung ISIS. Sebagian besar dari mereka yang pro-ISIS itu adalah anak-anak muda.
Melihat fenomena memprihatinkan seperti itulah, kita perlu mengapresiasi para pembaharu Islam di atas. Tahlilan untuk Djohan Effendi dan Meneladani Para Pembaharu Islam itu dimaksudkan untuk mengingatkan kita bangsa Indonesia bahwa pemikiran mereka tentang Islam, Keindonesiaan, Modernitas, dan Kebhinekaan harus kita hidupkan kembali. Jangan sampai tergerus pemikiran Islam radikal yang akan merobek kebhinnekaan, Pancasila, dan NKRI.
Editor : Administrator