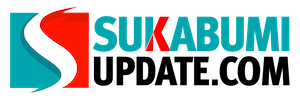SUKABUMIUPDATE.com - Ada sesuatu yang harus segera direnungkan ketika Direktur United Nations Development Programme (UNDP) atau Badan Program Pembangunan PBB, Achim Steiner mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dan lingkungan adalah sebuah paradoks.
Steiner memberi contoh soal bencana tumpahnya minyak di Teluk Meksiko Amerika Serikat pada tahun 2010 lalu yang notabene mendorong pertumbuhan ekonomi, namun justru menyisakan kerusakan lintas generasi bagi masyarakat di sekitar.
Dalam sebuah wawancara dengan media Jerman Deutsche Welle pada akhir Januari 2021 lalu, Steiner mengungkapkan bahwa akar masalahnya terletak pada persepsi kemakmuran yang selalu berkutat pada sisi finansial, tetapi melupakan ruang hidup dan kemanusiaan.
Akibatnya, kerusakan lingkungan mendapat toleransi sebagai jalan menuju kemakmuran tersebut. Ia menyebut, saat ini para ekonom dari berbagai disiplin ilmu sedang berupaya menemukan rumusan yang lebih baik bagi konsep pembangunan manusia.
Steiner menjelaskan bahwa paradigma soal pembangunan manusia yang terikat dengan pertumbuhan ekonomi telah terjadi pada abad 20 ini.
Pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan produk domestik bruto menjadi faktor utama yang sekarang digunakan untuk mengukur pembangunan, kemajuan, dan keberhasilan umat manusia. Namun telah lama model tersebut mengabaikan sejumlah elemen irasional dalam pengukurannya.
Misalnya, tumpahan minyak raksasa memang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi karena dapat menyerap uang dalam jumlah besar dan ikut menyumbang pertumbuhan PDB. Namun ada biaya kerusakan terhadap masyarakat, lingkungan, flora dan fauna, serta ekosistem yang tidak lagi dapat dipulihkan.
Oleh karena itu, dalam beberapa tahun terakhir, beragam disiplin ilmu ekonomi dan bidang ilmu pertumbuhan berkelanjutan berupaya mencari metode yang lebih baik untuk mengukur pembangunan manusia.
Steiner mengatakan, kepunahan spesies, kematian prematur tujuh juta manusia per tahun menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO), atau polusi di dalam dan di luar ruangan menjadi dampak dari sempitnya model pengukuran dan cara manusia mendefinisikan opsi-opsi pembangunan.
Perjanjian Paris sebagai Titik Awal
Ini merupakan perjanjian internasional yang mengikat secara hukum tentang perubahan iklim. Perjanjian ini diadopsi oleh 196 pihak pada Konferensi Kerangka Perubahan Iklim 21 di Paris pada 12 Desember 2015 dan mulai berlaku pada 4 November 2016.
Melansir dari laman resmi United Nations Climate Change, tujuan dari Perjanjian Paris ini adalah untuk membatasi pemanasan global hingga di bawah 2 atau bahkan 1,5 derajat Celcius dibandingkan dengan tingkat pra-industri.
Dalam mencapai tujuan jangka panjang tersebut, negara-negara harus mencapai puncak emisi gas rumah kaca global secepat mungkin untuk menuju dunia yang netral iklim pada pertengahan abad.
Perjanjian ini menjadi hal yang penting dalam proses perubahan iklim multilateral karena untuk pertama kalinya ada perjanjian yang mengikat seluruh negara agar memiliki tujuan yang sama untuk berupaya memerangi perubahan iklim dan beradaptasi dengan dampaknya.
Namun Perjanjian Paris ini memerlukan transformasi ekonomi dan sosial untuk dapat dilaksanakan. Pada tahun 2020 kemarin, negara-negara di dunia mengajukan rencana aksi iklim mereka yang disebut Nationally Determined Contributions (NDC).
Melihat Komitmen Indonesia
Indonesia sendiri menjadi salah satu negara yang menandatangani Perjanjian Paris tersebut. Bahkan Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang langsung mendepositkan instrumen ratifikasi.
Mengutip dari situs Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Siti Nurbaya Bakar menegaskan bahwa bergabungnya Indonesia ke dalam 55 negara pertama yang melakukan ratifikasi adalah karena lingkungan hidup menjadi hal yang penting sesuai UUD 1945. NDC Indonesia sendiri mencakup aspek mitigasi dan adaptasi.
Pada periode pertama, target NDC Indonesia adalah mengurangi emisi sebesar 29 persen dengan upaya sendiri dan hingga 41 persen jika ada dukungan internasional dari kondisi tanpa ada aksi (business as usual) pada tahun 2030.
Target tersebut akan dicapai melalui sektor kehutanan, energi, limbah, proses industri dan penggunaan produk, serta pertanian. Sementara komitmen NDC Indonesia untuk periode selanjutnya ditetapkan berdasarkan kajian kinerja dan harus menunjukkan peningkatan dari periode sebelumnya.
Tetapi dalam laporan terbaru Climate Change Performance Index 2021 disebutkan bahwa kebijakan iklim Indonesia dinilai belum selaras dengan Perjanjian Paris.
Laporan yang dirilis New Climate Institute, Climate Action Network, dan German Watch tersebut mengungkapkan bahwa Indonesia menempati peringkat 24 dan masih masuk dalam kategori sedang dalam indeks kinerja perubahan iklim 2021.
Penentuan peringkat ini berdasarkan pada kinerja agregat dari suatu negara yang dimasukkan ke dalam 14 indikator dan empat kategori, yakni emisi gas rumah kaca, energi terbarukan, penggunaan energi, dan kebijakan iklim.
Rinciannya, Indonesia masuk peringkat sedang untuk kategori emisi dengan nilai 53,49, peringkat tinggi untuk kategori energi terbarukan dengan nilai 51,43, peringkat tinggi untuk kategori penggunaan energi dengan nilai 69,47, peringkat sedang dalam upaya mitigasi dan kebijakan iklim secara keseluruhan.
Penurunan emisi di Indonesia yang terjadi pada tahun 2020 lalu disebabkan pengaruh Pandemi Covid-19, musim yang lebih basah, dan berkurangnya pembakaran hutan di tahun tersebut.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo dalam pidatonya pada acara Climate Adaptation Summit (CAS) 2021 tanggal 26 Januari kemarin mengatakan bahwa perubahan siklus iklim mengharuskan petani dan nelayan beradaptasi menghadapi ketidakpastian.
Ia mengatakan bahwa meningkatnya permukaan laut membuat penduduk pesisir dan pulau kecil untuk tetap bisa bertahan. Meningkatnya bencana alam, termasuk banjir dan kekeringan pun mengharuskan rakyat bersiap siaga.
Jokowi juga menuturkan bahwa Pandemi Covid-19 membuat tantangan semakin kompleks dan berat, sehingga seluruh negara harus memenuhi kontribusi NDC. Ia menyebut, Indonesia telah memutakhirkan NDC untuk meningkatkan ketahanan dan kapasitas adaptasi.
Jokowi menjelaskan bahwa Indonesia melibatkan masyarakat untuk mengendalikan perubahan iklim melalui program "Kampung Iklim" yang mencakup 20.000 desa di tahun 2024 dan memajukan pembangunan hijau.
Namun dalam laporan Greenpeace pada akhir Januari 2021 dikatakan bahwa NDC Indonesia justru masih belum ambisius.
Target pengurangan emisi karbon dinilai masih jauh dari mencukupi untuk mencegah kenaikan temperatur global. Bahkan jika seluruh negara di dunia menerapkan target NDC Indonesia, maka kenaikan temperatur global akan mencapai 4 derajat Celcius.
Selain itu, komitmen iklim Indonesia pun bertentangan dengan pengesahan UU Minerba dan UU Cipta Kerja yang semakin tidak memprioritaskan perlindungan lingkungan dengan dalih pertumbuhan ekonomi. Bencana banjir di Kalimantan Selatan seharusnya menjadi peringatan bagi pemerintah akan potensi dampak dari kedua peraturan tersebut.
Bentuk deforestasi yang didukung oleh perluasan perizinan tambang dan perkebunan skala besar (industri sawit dan bubur kertas) dan penebangan, telah berdampak pada Daerah Aliran Sungai atau DAS Barito. Belum lagi soal bentang alam yang semakin sensitif terhadap peristiwa iklim seperti kekeringan dan curah hujan yang intensif.
Greenpeace mencatat bahwa kegiatan ekstraksi bahan bakar fosil batu bara pun justru memperoleh banyak keistimewaan untuk semakin merambah hutan Tanah Air.
Indonesia sekarang ini masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil, khususnya sektor energi. Batu bara masih menguasai penyediaan listrik di Indonesia, yakni sebesar 64 persen atau 28 Giga Watt dan diperkirakan menghasilkan emisi sekitar 168 juta ton CO2.
Selain itu, menurut Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2019-2028, Pemerintah Indonesia juga berencana untuk menambah kapasitas PLTU batu bara sebesar dua kali lipat dalam sepuluh tahun mendatang, yakni 27 Giga Watt. Hal ini akan membuat jumlah emisi karbon semakin meningkat dan menjauhkan Indonesia dari target NDC-nya.
Dengan membangun PLTU batu bara baru, emisi karbon yang akan dihasilkan juga bahkan akan terkunci hingga 40 tahun mendatang atau selama masa operasi PLTU. Hal itu juga bertentangan dengan target Perjanjian Paris, di mana IPCC mendorong semua negara untuk mengurangi 80 persen PLTU existing di tahun 2030 untuk bisa mencapai target 1,5 derajat Celcius.
Membangun Paradigma Baru
Steiner menuturkan bahwa manusia saat ini harus mengubah cara pandang terhadap infrastruktur lingkungan dan ekologis, yaitu berinvestasi pada lingkungan, pemulihan lahan, menghentikan kerusakan hutan, dan kerusakan sungai-sungai atau ekosistem air.
Pada akhirnya manusia harus menyambut paradigma baru untuk melibatkan penghitungan seluruh komponen tersebut ke dalam sistem statistik perekonomian nasional.
Pasalnya, jika biaya hilangnya aset-aset lingkungan turut dihitung dalam neraca ekonomi nasional, maka manusia akan melihat lahirnya kebijakan baru serta arus investasi dan pembangunan yang lebih rasional.
Steiner mengungkapkan bahwa dalam membangun paradigma baru ini memang memerlukan dukungan politik yang baik, meskipun hal itu ibarat mata uang yang elusif.
Masyarakat mungkin dapat menyerahkan tanggungjawab ini kepada para politisi atau pejabat negara, namun dalam negara demokratis misalnya, para politisi terikat pada kepentingan jangka pendek dan mereka hanya akan berani untuk berkomitmen ketika paradigma baru ini dapat membantunya meraup dukungan elektoral.
Namun Steiner menegaskan bahwa umat manusia sudah tiba di batas kemampuan bumi. Jika manusia sudah tidak mampu memisahkan pertumbuhan ekonomi global dari jejak emisi, maka manusia akan binasa akibat dampak perubahan iklim yang sudah tidak dapat dihindari, bahkan tidak bisa dipulihkan.
Di sisi lain, Steiner justru optimis bahwa perekonomian masa depan akan lebih minim emisi, polusi, dan efisien dalam menggunakan sumber daya. Hal ini harus dibaca dalam proses perencanaan bisnis di sejumlah sektor teknologi demi bisa berdaya saing di pasar masa depan. Salah satunya terjadi pada rantai produksi industri otomotif global saat ini dengan adanya perusahaan kendaraan listrik, Tesla.
Pada Juni 2020 lalu, Tesla sempat menjadi perusahaan mobil paling berharga di dunia dan berhasil mengalahkan Toyota Jepang akibat lonjakan harga sahamnya. Hal itu merupakan prestasi yang mengesankan karena Tesla adalah salah satu model yang berbeda dari produsen mobil di zaman modern.
Tesla, Inc, pembuat mobil Silicon Valley memperoleh penilaian pasar dari 190,12 miliar USD dan tumbuh sebesar 8,97 persen. Kemudian Toyota mengikuti 182,27 miliar USD (+ 0,32 persen), dan Volkswagen milik Jerman tertinggal lebih dari 100 miliar untuk berada di posisi ketiga. Valuasi mencapai 81,72 miliar USD setelah menghadapi kejatuhan 4,70 persen.
Selanjutnya Honda jauh di belakang di 48,42 miliar USD (+ 0,47 persen). Grup Daimler Jerman (yang memiliki Mercedes-Benz) dihargai 45,18 miliar USD (-4,41 persen), disusul Ferrari 43,30 miliar USD (+ 0,67 persen). Sementara BMW Group mencatat 41,87 miliar USD dan penurunan sekitar 3,41 persen.
Pemilik Tesla, Elon Musk bahkan sempat dinobatkan sebagai orang terkaya di dunia. Meskipun dalam laporan Forbes pada 12 Januari 2021 kemarin disebutkan bahwa Musk disalip CEO Amazon, Jeff Bezos.
Posisi Musk menurun setelah kekayaannya tergerus hampir 14 miliar USD atau Rp 197,40 triliun (kurs Rp 14.100) hanya dalam satu hari. Pada Senin, 11 Januari 2021 saham Tesla turun hampir 8 persen dan mendorong kekayaan bersih Musk turun 13,5 miliar USD menjadi 176,2 miliar USD.
Saat ini kekayaan Musk berkisar 6 miliar USD di belakang Bezos yang memiliki kekayaan bersih 182,1 USD. Kekayaan bersih tersebut dihitung setelah saham Amazon turun lebih dari 2 persen pada Senin kemarin.
Oleh karena itu, Steiner berpesan bahwa pasar uang adalah sesuatu yang tidak loyal karena dapat mengubah loyalitasnya dengan cepat. Sehingga pertanyaannya sekarang adalah seberapa cepat manusia bisa membebaskan diri dari warisan ekonomi masa lalu dan secara aktif membidani perekonomian masa depan.
Editor : Oksa Bachtiar Camsyah