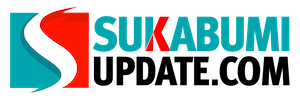SUKABUMIUPDATE.com - Perhelatan MotoGP di Sirkuit Internasional Mandalika pada Ahad, 20 Maret 2022, menyisakan cerita menarik soal pawang hujan bernama Rara Istiani Wulandari. Tampilnya Mbak Rara menjadi perbincangan di media sosial Indonesia dan luar negeri. Bahkan, akun resmi MotoGP pun ikut mengomentarinya.
Silang pendapat muncul terhadap aksi pawang hujan tersebut, terutama dengan yang menyambungkannya ke persoalan kebenaran dan kepercayaan. Namun, di luar kontroversi yang terjadi, tak bisa dipungkiri profesi pawang hujan memang ada dan sering digunakan dalam perhelatan di banyak wilayah nusantara, termasuk Sukabumi.
Sejarah Pawang Hujan di Sukabumi
Dalam masyarakat Sunda, pawang hujan biasanya diperlukan saat ada acara hajatan seperti pernikahan, selametan, sunatan, bahkan kegiatan pemerintah yang digelar di luar ruangan (outdoor). Pada dasarnya, pekerjaan mereka bukan menghentikan hujan, tetapi menahan hujan untuk sementara atau memindahkan hujan ke area lain.
Pengamat sejarah Sukabumi Irman Firmansyah mengatakan, di Cianjur Selatan, di mana dia sempat tinggal, ada Haji Alwan yang dikenal pawang hujan jitu (istilahnya tara misleuk). Caranya unik. Selain berdoa dan mendoakan Syeikh Abdul Qadir Jaelani, dia menggantung batu asahan ke para seuneu (tempat menyimpan kayu bakar di atas tungku).
Tak hanya di Cianjur, Irman juga menyebut tokoh serupa ada di Sukabumi. Ada beberapa nama seperti Bah Uto di Kampung Bandang, Kecamatan Cireunghas, Kabupaten Sukabumi. Kemudian, Ibu Haji Masitoh dan Haji Ridwan yang juga di Kampung Kukulu, Kecamatan Cireunghas. Ketiganya dikenal sebagai pawang hujan.
"Banyak yang beranggapan mereka berkomunikasi dengan malaikat pembawa angin. Prosesnya sendiri konon memang mendorong awan dengan perantara angin. Sebagian pawang, dalam prosesinya memang tidak pernah memakai baju, alasannya karena anginnya panas," kata Irman kepada sukabumiupdate.com, Selasa (22/3/2022).
Menurut Irman, pawang hujan merupakan kearifan lokal yang umum di nusantara. Hampir di semua daerah ada pawang hujan sebagai salah satu profesi langka.
Dalam masyarakat Sunda seperti Sukabumi, disebut tukang sarang hujan. Nyarang bisa jadi istilah yang sudah cukup tua, mengingat di belahan pulau Jawa lainnya disebut sebagai Nyarang Udan. Sementara di Madura disebut Nyarang Ojhen. Bahkan di Sumatera Barat, ada istilah Manyarang hari sebagai upacara untuk menangkal hujan.
 Mbak Rara, pawang hujan di MotoGP Mandalika 2022 - (Arief Apriadi/Suara.com)
Mbak Rara, pawang hujan di MotoGP Mandalika 2022 - (Arief Apriadi/Suara.com)Profesi ini kerap dikaitkan dengan hal mistis dan gaib karena memang sulit dijelaskan secara logika. Irman yang juga Ketua Yayasan Dapuran Kipahare menyebut sebagian menggunakan pawang hujan karena memang percaya akan kemampuannya. Sebagian lagi menganggap hanya sebagai antisipasi antara percaya dan tidak percaya.
Tradisi pawang hujan ditengarai sudah ada sejak zaman dahulu, mengingat wilayah Sunda adalah wilayah tropis yang sering terjadi hujan. Berbeda dengan Arab misalnya, yang jarang hujan sehingga tradisi di sana adalah meminta hujan. Namun, belum dipastikan apakah, misalnya, di zaman kerajaan Sunda Padjadjaran sudah ada profesi ini, mengingat istilah tukang nyarang hujan tidak tercantum dalam naskah dan prasasti Sunda, termasuk dalam naskah Siksa Kandang Karesian yang memuat nama-nama profesi pada masa tersebut.
"Atau bisa jadi ada nama tertentu yang belum dapat ditemukan atau diungkap oleh para peneliti," ucap Irman yang juga penulis buku "Soekaboemi the Untold Story".
Profesi pawang hujan kemungkinan besar sudah ada sejak dimulainya budaya pentas outdoor yang ditonton secara massal. Pasalnya, masyarakat Sunda adalah masyarakat agraris yang berladang (sawah kering), di mana hujan justru diperlukan untuk mengairi ladang secara alami. Berbeda, sesudah munculnya budaya sawah di masa Mataram dan Vereenigde Oost Indische Compagnie atau VOC yang menggunakan teknik penggenangan air dengan penahan pematang, di mana hujan diperlukan secukupnya.
Irman menjelaskan budaya asli peladang juga tidak memungkinkan kegiatan massal mengingat budaya huma yang berjauhan dan berpindah-pindah menyebabkan longgarnya hubungan sosial, sehingga diperkirakan proses selamatan hanya melibatkan unit keluarga kecil. Masyarakat Sunda juga dikenal sebagai masyarakat ekologis yang selalu berdampingan dengan alam tanpa saling mengganggu. Dengan menahan dan mengalihkan proses alam, dapat mengganggu keseimbangan di tempat lain.
Merujuk pada Edi Suhardi Ekadjati, Irman mengatakan masyarakat Sunda menganggap seluruh kehidupannya tidak dapat dipisahkan dari kosmos (kosmik klasifikatoris). Setiap kejadian dan hal-hal yang ada di dalam alam semesta, mempunyai tempatnya sendiri-sendiri melalui konsep madhab papat kalima pancer.
"Jika mengacu pada pendapat tersebut, maka seluruh kehidupan dalam masyarakat Sunda pada dasarnya ditujukan untuk memelihara keseimbangan yang ada di alam semesta," katanya.
Sistem pengetahuan dalam budaya Sunda memiliki esensi cabang-cabang pengetahuan, misalnya tentang alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, ruang, dan waktu. Pengetahuan ini digunakan untuk mencari keselamatan, rezeki, dan mata pencaharian yang membentuk konsep ikhtiar. Misalnya, pengetahuan Bintang Wuluku yang muncul pada waktu permulaan musim hujan sebagai ikhtiar dalam pertanian.
Kemdian, pengetahuan tentang buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan yang dihubungkan dengan ikhtiar penyembuhan penyakit. Terkait waktu dan pelaksanaan juga muncul ikhtiar penghitungan hari baik yang dilakukan tanpa mengganggu proses alam, cukup dengan memilih waktu dan tempat sesuai tanda-tanda alam, bukan merekayasa proses alam.
Keseimbangan ini dipertahankan lewat beragam upacara berupa ritual magis dan saling memberi. Ketika terjadi perubahan budaya dari nomaden menjadi menetap, termasuk perubahan budaya ladang menjadi sawah, tentu mengubah strukur sosial yang menciptakan kumpulan manusia berupa babakan, kampung yang memungkinkan kegiatan massal.
Perubahan ini membutuhkan ikhtiar baru berupa pengetahuan untuk mempermudah kegiatan. Sehingga, kata Irman Irman, diperkirakan pada masa inilah mulai muncul ikhtiar untuk mencegah hujan dalam kegiatan-kegiatan tertentu yang mengumpulkan massa cukup banyak. Meski baru kemungkinan, tetapi cukup menarik untuk dikaji.
Pawang Hujan Era Kolonial
Literatur yang berkembang mengenai pawang hujan atau tukang sarang hujan di wilayah Sunda, justru berkembang di masa kolonial. Masyarakat Eropa pada waktu itu menganggap pekerjaan pawang hujan hanyalah klenik, namun dalam praktiknya mereka kerap menghormati kebiasaan masyarakat dengan melakukan selamatan dalam setiap kegiatan.
"Kegiatan tersebut salah satunya melibatkan keberadaan pawang hujan. Sehingga, kajian mengenai pawang hujan juga dilakukan oleh beberapa peneliti Belanda serta penulis lokal yang tertarik dengan fenomena ini," kata Irman.
Pengarang Belanda, A.C. Deenik, pada 1910 meenyebut saat masa musim penghujan yang terjadi terus-menerus, ada ikhtiar yang dilakukan orang kampung yatu menyarang hujan. Sebaliknya, apabila musim kemarau dan ingin hujan turun, harus memandikan kucing. Fenomena teknik pawang juga sejak zaman dahulu berbeda-beda.
Teknik tersebut misalnya Raden Haji Hasan Mustafa pada 1913 menulis bahwa ritual menolak hujan di antaranya dengan jampi-jampi supaya tidak turun hujan dan pawangnya tidak mandi dan tidak pakai baju. Sementara H.C. Croes pada 1922 menyebutkan syarat untuk menyarang hujan adalah dengan mengacungkan tombak warisan pusaka leluhur ke atas langit, dilengkapi kemenyan dan sesajen. Sementara Satjadibrata pada 1948 menyebutkan ritual nyarang hujan dengan menancapkan alu di tanah kemudian ditutup kain serta diberi jampi-jampi.
Kemampuan menangkal hujan ini juga berkembang di masyarakat dengan beragam cara, termasuk di kalangan pesantren pada masa tersebut. J. Cats, kata Irman, pada 1922 menyebut kiai sering mewariskan keris yang mempunyai khasiat salah satunya menolak hujan sehingga mampu menolong orang.
"Fenomena di atas menjadi bukti di sebagian masyarakat Sunda terutama di pedesaan, unsur agama dan kepercayaan asli sudah terintegrasikan dalam sistem kepercayaan. Dalam perkembangannya, kemampuan menangkal hujan juga kerap dimiliki oleh pementas seperti dalang," beber Irman.
G.A.J. Hazeu menyebut dalang mempunyai profesi rangkap sebagai pawang hujan karena pementasan wayang memerlukan cuaca yang bagus bagi masyarakat yang menonton.
Hingga kini profesi pawang hujan ini masih ada. Irman mengaku masih ingat ketika mengadakan sebuah kegiatan beberapa tahun lalu, menemukan garam yang ditabur di beberapa sudut gedung. Ketika ditelusuri, ternyata salah satu panitia melakukan ritual mencegah hujan karena kegiatan dilakukan di musim hujan.
"Ya di luar kontroversinya, fakta mengenai pawang hujan ini memang masih ada di sekitar kita dan sebagian masyarakat masih menggunakannya. Persoalan pawang Mandalika yang menarik sebenarnya adalah strategi memviralkan Sirkuit Mandalika-nya, yaitu dengan hanya menggunakan pawang hujan yang diperkirakan akan viral baik dengan keunikan lokalnya bagi masyarakat internasional maupun kontroversinya terkait kepercayaan," tutup Irman.
Sebelumnya, Badan Meterologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG telah memberikan penjelasan mengenai fenomena hujan yang berhenti ketika pawang hujan melakukan aksinya. Ini merujuk kepada aksi Mbak Rara saat perhelatan MotoGP di Sirkuit Internasional Mandalika.
Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto memberikan penjelasan mengenai fenomena tersebut. Guswanto mengatakan, kearifan lokal tak bisa dicampuradukkan dengan sains. Secara saintifik, sulit dijelaskan bila hujan berhenti karena faktor pawang hujan. "Ya sebenarnya kalau dilihat pawang hujan itu adalah suatu kearifan lokal yang dimiliki masyarakat. Secara saintifik itu sulit untuk dijelaskan," kata dia dikutip dari suara.com.
Guswanto menjelaskan BMKG sudah memberikan prakiraann cuaca saat race MotoGP Mandalika berlangsung. Hal tersebut karena bibit sikon tropis 93F yang dampaknya memberikan potensi pertumbuhan awan hujan di Mandalika. BMKG pun sudah memberikan informasi mengenai prakiraan cuaca di Mandalika dalam kurun tiga hari.
"Dan buktinya, kan dari awal pawang itu sudah bekerja, tapi kan gak berhenti juga. Artinya itu. Jadi sebenarnya kemarin waktu berhentinya, itu bukan karena pawang hujan. Karena durasi waktunya sudah selesai," jelasnya. "Kalau dilihat prakiraan lengkap di tanggal itu memang selesai di jam itu. Kira-kira jam 16.15 itu sudah selesai, tinggal rintik-rintik itu bisa dilakukan balapan kalau dilihat dari prakiraan nasional analisis dampak yang kita miliki BMKG," imbuh Guswanto.
Editor : Oksa Bachtiar Camsyah